
Essai Lingkungan Mahar Prastowo
Indonesiana | Tempo
Ketika matahari pagi belum sepenuhnya mengusir kabut rendah yang menghiasi langit Jakarta Timur, suara gemericik air di pinggir bantaran Sungai Cipinang memanggil perhatian. Bukan karena gemuruh arus deras - tetapi karena riak kecil yang menyentuh ranting, menyapu dedaunan yang berguguran, memberi tahu kita: sungai ini masih hidup. Namun, hidup yang rapuh, terus terancam.
Titik balik
Sungai Cipinang, membentang sepanjang lebih dari 30 km dari Depok ke Jakarta Timur, telah lama menjadi saksi bisu dinamika urbanisasi ibu kota - pemukiman padat, aktivitas industri, sampah plastik, sedimentasi, hingga ancaman banjir yang kerap melanda.
Tumpukan sampah, aliran tersumbat, dan air yang keruh bukan sekadar masalah estetika; ini soal hidup bersama, soal ruang publik yang dilupakan, soal sungai yang kehilangan fungsi ekologisnya.
Aksi kolaborasi: ketika tangan-tangan bersatu
Baru-baru ini, sebuah gerakan bergerak: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT Vale Indonesia (anak usaha dari grup tambang yang masuk dalam MIND ID), pemerintah daerah, komunitas peduli sungai, dan warga Kelurahan Kebon Pala bersinergi ― sebuah kolaborasi publik-swasta-komunitas yang bukan sekadar seremoni.
Aksi ini mencakup: pengangkatan sedimen dan sampah di badan sungai, penanaman pohon di bantaran, hingga penguatan komunitas yang kelak akan menjadi “pengawas” setempat.
Dalam pidatonya, Wakil Menteri LH menyebut bahwa “menjaga sungai berarti menjaga sumber kehidupan.”
Mengapa ini penting
Karena sungai bukan sekadar aliran air. Dalam lanskap kota yang semakin semen, sungai adalah serat kehidupan: saluran air, ruang hijau, penahan banjir, sekaligus agen sosial yang menghubungkan manusia dengan alam. Saat fungsi itu hilang - maka kita kehilangan lebih dari air yang mengalir; kita kehilangan rasa memiliki, rasa sadar, rasa tanggung jawab.
Apalagi di kawasan pemukiman seperti Kebon Pala, di mana siapa pun bisa melihat sampah terbawa arus setiap hujan deras. Disiplin masyarakat dan sistem pengelolaan sungai yang lemah telah menjadikan banjir sebagai keniscayaan, bukan kejadian luar biasa.
Tantangan dan durabilitas
Namun kini datang tantangan: bagaimana menjamin bahwa gerakan ini tidak berhenti saat potret fotografinya hilang dari feed medsos? Bagaimana agar penanaman pohon itu tumbuh, trash-boom bekerja, dan komunitas tetap aktif?
Deputi PLKLH menegaskan bahwa targetnya bukan sekadar aksi sekali jadi, melainkan “gerakan berkelanjutan”.
Nilai TSS (Total Suspended Solid) harus diukur, standar mutu air harus dipenuhi - tapi siapa yang rutin mengawal? Sistem kelembagaan siapa yang mengikat? Ini yang kerap menjadi lubang: aksi tampak, monitoring lemah, kemudian semuanya mengendap menjadi rutinitas belaka.
Kisah warga: dari penonton menjadi pelaku
Di Kebon Pala, seorang ibu muda bernama Siti (nama samaran) menggenggam sapu plastik, turun ke bantaran sungai. “Dulu saya cuma lihat sampah lewat tiap hujan, sekarang saya ikut mengangkat,” ujarnya sambil menunjuk tempat ikan-ikan kecil mulai muncul lagi di air yang lebih tenang.
Kisah sederhana ini tetap penting: karena kolaborasi tidak hanya soal instansi atau korporasi besar, tetapi soal orang-orang kecil yang mau berubah. Ketika warga merasa punya bagian dari sungai, maka sungai bukan lagi “barang orang lain”.
Betapa pun sekecil - satu pohon, satu sapu, satu komunitas
Saya teringat kalimat sederhana yang muncul di pernyataan korporasi:
“Sungai yang bersih berarti kehidupan yang berkelanjutan. Kolaborasi hari ini membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari aksi sederhana - dari satu pohon yang ditanam, satu sampah yang diangkat, hingga satu komunitas yang berdaya.”
Kata-kata itu bukan sekadar retorika. Mereka mengandung kebenaran: perubahan besar bermula dari hal kecil, dan terus berulang.
Namun yang paling penting: perubahan itu tidak berhenti ketika foto diunggah. Ia harus tertanam - di hati warga, di mekanisme kota, di kebijakan pemerintah, dan di nilai perusahaan.
Untuk Jakarta, untuk masa depan
Jakarta tidak bisa terus melihat sungai sebagai jalur dibuang, tetapi sebagai ruang hidup bersama. Bila kita berhasil mewujudkan model di Sungai Cipinang, maka kota ini bisa menciptakan rumah bagi air - bukan penjara bagi air yang tersekat.
Model ini dapat dijadikan contoh di bantaran sungai lain, di kota-kota lain. Dengan kolaborasi yang tulus, bukan sekadar ceremonial. Dengan peran warga, bukan hanya observasi. Dengan tanggung jawab jangka panjang, bukan kampanye satu kali.
Tips bagi pembaca - bagaimana Anda bisa ikut
1. Kenali sungai lokal Anda - cari tahu siapa “pemilik” administratif bantaran di wilayah Anda.
2. Gabung komunitas atau bentuk komunitas kecil - misalnya “Teman Sungai RW 05” yang rutin lakukan bersih-bersih.
3. Dorong instansi & perusahaan terlibat nyata - ajukan proposal sederhana: misalnya penanaman pohon, pemasangan trash-boom kecil, monitoring kualitas air.
4. Lakukan monitoring sederhana - catat sebelum-sesudah aksi: jumlah sampah, kondisi air, partisipasi warga.
5. Lakukan edukasi di lingkungan sekitar - misalnya bahwa membuang sampah ke sungai berarti membajak ruang hidup kita sendiri.
Jika setiap warga Jakarta melakukan sedikit hal nyata, maka sungai-sungai kita bisa berubah - dari aliran terabaikan menjadi arteri kehidupan kota. Karena, seperti yang sudah dikatakan: menjaga sungai berarti menjaga sumber kehidupan.
[mp]










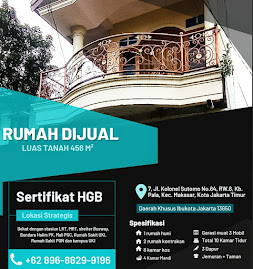
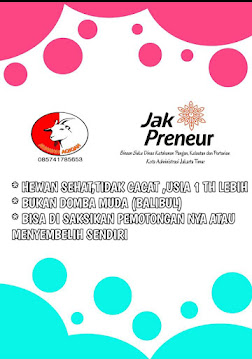






0 Komentar