Oleh Mahar Prastowo
Dalam telaah antropolog Clifford Geertz tentang masyarakat Jawa, ada tiga lapis kekuasaan yang hidup berdampingan: negara, pasar, dan "orang kuat". Yang terakhir ini—disebutnya strongmen—muncul ketika negara terlalu jauh dan pasar terlalu liar. Mereka mengambil peran sebagai penengah, sekaligus pemangsa.
Premanisme di Indonesia tumbuh dari kekosongan—vacuum of power—yang terus dipelihara oleh sistem. Ia tidak dilahirkan oleh kejahatan, tetapi oleh kebutuhan akan ketertiban yang tak diberikan secara adil. Seperti dalam dunia wayang, ketika raja lemah dan dalang tak jelas, muncullah tokoh-tokoh seperti Dursasana dan Sengkuni, yang mengatur lewat tipu daya dan otot. Dan anehnya, masyarakat tetap menonton dan bertepuk tangan.
Ong Hok Ham, sejarawan yang tajam sekaligus lirih, pernah menulis bahwa sejak zaman kolonial, negara di Indonesia adalah entitas yang “jauh di atas menara gading”. Di bawahnya, rakyat membangun aturan sendiri: dari paguyuban sampai jago kampung. Maka tak heran, premanisme bukan hanya bentuk kriminalitas, tapi semacam order alternatif yang kadang lebih cepat, lebih efektif, meski tidak adil.
Tapi kita juga melihat wajah premanisme yang baru—di layar kaca, di sinetron sore hari, bahkan di bioskop. Serial "Preman Pensiun" membawa narasi lain: tentang preman yang lelah, yang ingin bertobat, yang ingin kembali menjadi manusia biasa. Tapi dunia tak semudah itu. Mereka yang ingin keluar dari lingkaran kekuasaan informal sering kali tidak diberi jalan. Mereka diingatkan bahwa tak ada pensiun dalam dunia gelap, kecuali mati atau dibunuh.
Dan dalam film "Serigala Terakhir", kita melihat bagaimana preman-preman muda dijerat dalam loyalitas yang semu: kepada teman, kepada bos, kepada bayangan masa lalu. Kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang mereka pahami, karena hanya itu yang diajarkan kepada mereka sejak kecil.
Kini, ketika Polri mengibarkan bendera operasi dan menggandeng TNI serta pemerintah daerah, kita seakan menyaksikan panggung besar sedang dibersihkan. Tapi para penonton tahu, kadang panggung dibersihkan bukan untuk mengakhiri pertunjukan—melainkan untuk mengganti pemain.
Yang perlu kita tanyakan: setelah preman-preman ini disingkirkan, kepada siapa ruang kosong itu akan diwariskan? Apakah negara benar-benar hadir menggantikan peran mereka—dengan keadilan, dengan keberpihakan kepada yang lemah?
Ataukah akan muncul bentuk baru dari premanisme yang lebih rapi, lebih legal, lebih menguasai sistem?
Di akhir catatannya, Ong Hok Ham menulis bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah kekuasaan yang tidak pernah selesai menjelaskan dirinya sendiri. Dan mungkin, dalam labirin itu, kita baru menyadari: kadang yang disebut "preman" adalah cermin kecil dari negara itu sendiri—takut kehilangan kuasa, dan selalu menagih loyalitas dari rakyatnya.
Dan di suatu sudut kota yang senyap, seorang anak muda yang tumbuh dalam kekerasan hari ini mungkin tengah memegang surat panggilan. Bukan sebagai tersangka. Tapi sebagai calon aparat penegak hukum (APH). Dan sejarah, seperti biasa, hanya berputar pelan sambil tersenyum tipis.
_____
Penulis adalah jurnalis, pegiat komunitas warga, dan pengamat sosial perkotaan.








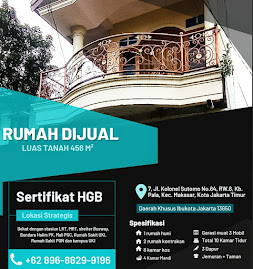
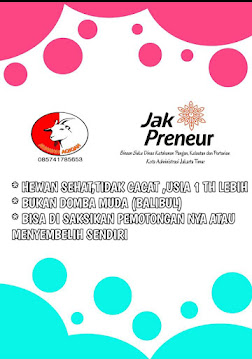






0 Komentar